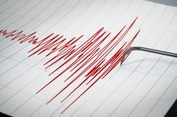Masalah Agraria dan HAM, Mengapa Tak Terpisahkan?

AWAL tahun 2022, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kebijakan pencabutan sekitar 2.078 izin konsesi lahan tambang dan mineral. Pencabutan izin itu dalam rangka perbaikan tata kelola pertanahan serta sumber daya alam (SDA).
Berbagai konsesi perusahaan yang dianggap tidak produktif, tidak mempunyai rencana kerja, dan tanahnya diterlantarkan menjadi sasaran utama pemerintah dalam kebijakan pencabutan izin tersebut.
Pemerintah juga mencabut 192 izin di sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektar, serta hak guna usaha (HGU) perkebunan seluas 34.448 hektar, yang setelah dilakukan penelusuran secara mendalam kini telah berstatus terlantar.
Langkah tersebut perlu diapresiasi. Maraknya konflik agraria yang terjadi di seluruh pelosok Tanah Air merupakan akibat beroperasinya perusahaan-perusahaan yang berperan sebagai pemilik konsesi lahan tersebut.
Baca juga:
Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, juga menyebut kasus-kasus konflik agraria merupakan kasus terbanyak kedua yang dilaporkan ke Komnas HAM hingga saat ini.
Urgensi penyelesaian berbagai kasus di sektor agraria juga merujuk pada laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) tahun 2023, yang menyebutkan bahwa situasi agraria di Tanah Air sepanjang tahun 2022 menunjukkan tren letusan konflik agraria yang tidak kunjung berkurang, bahkan meningkat.
Secara umum, KPA telah merilis sejumlah kasus konflik agraria yang kini telah mencapai 212 kasus sepanjang tahun 2022. KPA bahkan menyebut, kebijakan Presiden Joko Widodo dalam mencabut izin konsesi lahan tersebut masih diragukan keefektifannya bila dikaitkan dengan penyelesaian masalah agraria.
Hal itu karena tidak ada kejelasan apakah kebijakan pencabutan izin dan konsesi tersebut berkorelasi dengan lokasi-lokasi yang selama ini menjadi episentrum konflik agraria, ataupun dilakukan atas dasar koreksi dari ketimpangan penguasaan tanah yang terjadi di Tanah Air.
Pencabutan juga ditakutkan dapat dijadikan sebagai jalan baru bagi korporasi lainnya untuk dapat memperbaharui izin dan konsesi yang semakin berpotensi memperparah konflik agraria di Indonesia.
Kasus-kasus perampasan dan penyerobotan tanah masyarakat, serta berbagai polemik dari konflik agraria yang masih terjadi hingga saat ini seperti tidak ada habisnya.
Problematika agraria di Indonesia tampaknya setali tiga uang dengan masalah penegakan hak asasi manusia (HAM). Tanah merupakan bagian dari Bumi kita yang menyangkut hajat hidup sebagian besar masyarakat. Tanah sangat berkaitan dengan identitas masyarakat, sumber penghidupan, hak ekonomi, dan sosial budaya, sehingga pemanfaatannya harus mendapatkan atensi dan pengawasan negara.
Hal itu tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3, yang menyatakan bahwa... bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk memenuhi amanat UUD tersebut, hak-hak individu atau kelompok masyarakat terhadap tanah harus dilindungi, dipenuhi, dan dihargai negara.
Memahami Urgensi Masalah Agraria
Agar dapat memahami urgensi masalah agraria, masyarakat perlu mengetahui mengapa problematika ini merupakan bagian dari permasalahan hak asasi manusia. Bila dikorelasikan dengan isu HAM, menurut Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), terdapat beberapa aspek hak asasi manusia dalam isu agraria, di antaranya adalah pengentasan kemiskinan dan pembangunan, perdamaian, bantuan kemanusiaan, pencegahan dan pemulihan bencana, serta perencanaan kota dan pedesaan.
Selain itu, berdasarkan laporan dari FIAN International for the Hands on the Land for Food Sovereignty Alliance tahun 2017, terdapat beberapa faktor mengapa masalah agraria merupakan bagian dari permasalahan hak asasi manusia.
Pertama, masalah agraria dapat menimbulkan terjadinya kehilangan akses atau kendali masyarakat atas tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya tanpa adanya proses formal, sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan yang berujung pada timbulnya kekerasan.
Baca juga: Bereskan Konflik Agraria Butuh Kepemimpinan Politik Jokowi